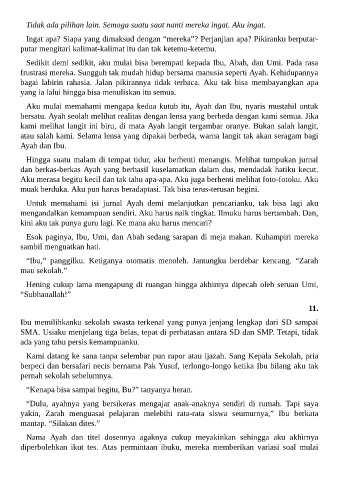Page 53 - Supernova 4, Partikel
P. 53
Tidak ada pilihan lain. Semoga suatu saat nanti mereka ingat. Aku ingat.
Ingat apa? Siapa yang dimaksud dengan “mereka”? Perjanjian apa? Pikiranku berputar-
putar mengitari kalimat-kalimat itu dan tak ketemu-ketemu.
Sedikit demi sedikit, aku mulai bisa berempati kepada Ibu, Abah, dan Umi. Pada rasa
frustrasi mereka. Sungguh tak mudah hidup bersama manusia seperti Ayah. Kehidupannya
bagai labirin rahasia. Jalan pikirannya tidak terbaca. Aku tak bisa membayangkan apa
yang ia lalui hingga bisa menuliskan itu semua.
Aku mulai memahami mengapa kedua kutub itu, Ayah dan Ibu, nyaris mustahil untuk
bersatu. Ayah seolah melihat realitas dengan lensa yang berbeda dengan kami semua. Jika
kami melihat langit ini biru, di mata Ayah langit tergambar oranye. Bukan salah langit,
atau salah kami. Selama lensa yang dipakai berbeda, warna langit tak akan seragam bagi
Ayah dan Ibu.
Hingga suatu malam di tempat tidur, aku berhenti menangis. Melihat tumpukan jurnal
dan berkas-berkas Ayah yang berhasil kuselamatkan dalam dus, mendadak hatiku kecut.
Aku merasa begitu kecil dan tak tahu apa-apa. Aku juga berhenti melihat foto-fotoku. Aku
muak berduka. Aku pun harus beradaptasi. Tak bisa terus-terusan begini.
Untuk memahami isi jurnal Ayah demi melanjutkan pencarianku, tak bisa lagi aku
mengandalkan kemampuan sendiri. Aku harus naik tingkat. Ilmuku harus bertambah. Dan,
kini aku tak punya guru lagi. Ke mana aku harus mencari?
Esok paginya, Ibu, Umi, dan Abah sedang sarapan di meja makan. Kuhampiri mereka
sambil menguatkan hati.
“Ibu,” panggilku. Ketiganya otomatis menoleh. Jantungku berdebar kencang. “Zarah
mau sekolah.”
Hening cukup lama mengapung di ruangan hingga akhirnya dipecah oleh seruan Umi,
“Subhanallah!”
11.
Ibu memilihkanku sekolah swasta terkenal yang punya jenjang lengkap dari SD sampai
SMA. Usiaku menjelang tiga belas, tepat di perbatasan antara SD dan SMP. Tetapi, tidak
ada yang tahu persis kemampuanku.
Kami datang ke sana tanpa selembar pun rapor atau ijazah. Sang Kepala Sekolah, pria
berpeci dan bersafari necis bernama Pak Yusuf, terlongo-longo ketika Ibu bilang aku tak
pernah sekolah sebelumnya.
“Kenapa bisa sampai begitu, Bu?” tanyanya heran.
“Dulu, ayahnya yang bersikeras mengajar anak-anaknya sendiri di rumah. Tapi saya
yakin, Zarah menguasai pelajaran melebihi rata-rata siswa seumurnya,” Ibu berkata
mantap. “Silakan dites.”
Nama Ayah dan titel dosennya agaknya cukup meyakinkan sehingga aku akhirnya
diperbolehkan ikut tes. Atas permintaan ibuku, mereka memberikan variasi soal mulai