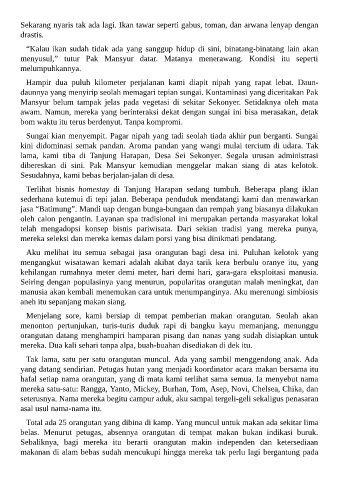Page 95 - Supernova 4, Partikel
P. 95
Sekarang nyaris tak ada lagi. Ikan tawar seperti gabus, toman, dan arwana lenyap dengan
drastis.
“Kalau ikan sudah tidak ada yang sanggup hidup di sini, binatang-binatang lain akan
menyusul,” tutur Pak Mansyur datar. Matanya menerawang. Kondisi itu seperti
melumpuhkannya.
Hampir dua puluh kilometer perjalanan kami diapit nipah yang rapat lebat. Daun-
daunnya yang menyirip seolah memagari tepian sungai. Kontaminasi yang diceritakan Pak
Mansyur belum tampak jelas pada vegetasi di sekitar Sekonyer. Setidaknya oleh mata
awam. Namun, mereka yang berinteraksi dekat dengan sungai ini bisa merasakan, detak
bom waktu itu terus berdenyut. Tanpa kompromi.
Sungai kian menyempit. Pagar nipah yang tadi seolah tiada akhir pun berganti. Sungai
kini didominasi semak pandan. Aroma pandan yang wangi mulai tercium di udara. Tak
lama, kami tiba di Tanjung Harapan, Desa Sei Sekonyer. Segala urusan administrasi
dibereskan di sini. Pak Mansyur kemudian menggelar makan siang di atas kelotok.
Sesudahnya, kami bebas berjalan-jalan di desa.
Terlihat bisnis homestay di Tanjung Harapan sedang tumbuh. Beberapa plang iklan
sederhana kutemui di tepi jalan. Beberapa penduduk mendatangi kami dan menawarkan
jasa “Batimung”. Mandi uap dengan bunga-bungaan dan rempah yang biasanya dilakukan
oleh calon pengantin. Layanan spa tradisional ini merupakan pertanda masyarakat lokal
telah mengadopsi konsep bisnis pariwisata. Dari sekian tradisi yang mereka punya,
mereka seleksi dan mereka kemas dalam porsi yang bisa dinikmati pendatang.
Aku melihat itu semua sebagai jasa orangutan bagi desa ini. Puluhan kelotok yang
mengangkut wisatawan kemari adalah akibat daya tarik kera berbulu oranye itu, yang
kehilangan rumahnya meter demi meter, hari demi hari, gara-gara eksploitasi manusia.
Seiring dengan populasinya yang menurun, popularitas orangutan malah meningkat, dan
manusia akan kembali menemukan cara untuk menumpanginya. Aku merenungi simbiosis
aneh itu sepanjang makan siang.
Menjelang sore, kami bersiap di tempat pemberian makan orangutan. Seolah akan
menonton pertunjukan, turis-turis duduk rapi di bangku kayu memanjang, menunggu
orangutan datang menghampiri hamparan pisang dan nanas yang sudah disiapkan untuk
mereka. Dua kali sehari tanpa alpa, buah-buahan disediakan di dek itu.
Tak lama, satu per satu orangutan muncul. Ada yang sambil menggendong anak. Ada
yang datang sendirian. Petugas hutan yang menjadi koordinator acara makan bersama itu
hafal setiap nama orangutan, yang di mata kami terlihat sama semua. Ia menyebut nama
mereka satu-satu: Rangga, Yanto, Mickey, Burhan, Tom, Asep, Novi, Chelsea, Chika, dan
seterusnya. Nama mereka begitu campur aduk, aku sampai tergeli-geli sekaligus penasaran
asal usul nama-nama itu.
Total ada 25 orangutan yang dibina di kamp. Yang muncul untuk makan ada sekitar lima
belas. Menurut petugas, absennya orangutan di tempat makan bukan indikasi buruk.
Sebaliknya, bagi mereka itu berarti orangutan makin independen dan ketersediaan
makanan di alam bebas sudah mencukupi hingga mereka tak perlu lagi bergantung pada