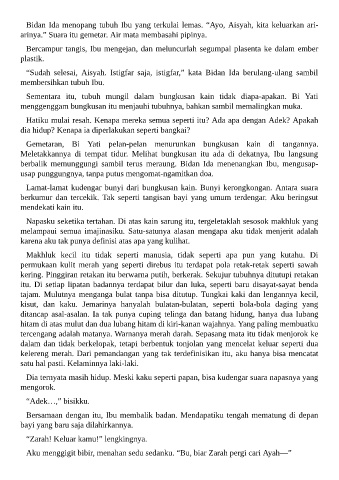Page 27 - Supernova 4, Partikel
P. 27
Bidan Ida menopang tubuh Ibu yang terkulai lemas. “Ayo, Aisyah, kita keluarkan ari-
arinya.” Suara itu gemetar. Air mata membasahi pipinya.
Bercampur tangis, Ibu mengejan, dan meluncurlah segumpal plasenta ke dalam ember
plastik.
“Sudah selesai, Aisyah. Istigfar saja, istigfar,” kata Bidan Ida berulang-ulang sambil
membersihkan tubuh Ibu.
Sementara itu, tubuh mungil dalam bungkusan kain tidak diapa-apakan. Bi Yati
menggenggam bungkusan itu menjauhi tubuhnya, bahkan sambil memalingkan muka.
Hatiku mulai resah. Kenapa mereka semua seperti itu? Ada apa dengan Adek? Apakah
dia hidup? Kenapa ia diperlakukan seperti bangkai?
Gemetaran, Bi Yati pelan-pelan menurunkan bungkusan kain di tangannya.
Meletakkannya di tempat tidur. Melihat bungkusan itu ada di dekatnya, Ibu langsung
berbalik memunggungi sambil terus meraung. Bidan Ida menenangkan Ibu, mengusap-
usap punggungnya, tanpa putus mengomat-ngamitkan doa.
Lamat-lamat kudengar bunyi dari bungkusan kain. Bunyi kerongkongan. Antara suara
berkumur dan tercekik. Tak seperti tangisan bayi yang umum terdengar. Aku beringsut
mendekati kain itu.
Napasku seketika tertahan. Di atas kain sarung itu, tergeletaklah sesosok makhluk yang
melampaui semua imajinasiku. Satu-satunya alasan mengapa aku tidak menjerit adalah
karena aku tak punya definisi atas apa yang kulihat.
Makhluk kecil itu tidak seperti manusia, tidak seperti apa pun yang kutahu. Di
permukaan kulit merah yang seperti direbus itu terdapat pola retak-retak seperti sawah
kering. Pinggiran retakan itu berwarna putih, berkerak. Sekujur tubuhnya ditutupi retakan
itu. Di setiap lipatan badannya terdapat bilur dan luka, seperti baru disayat-sayat benda
tajam. Mulutnya menganga bulat tanpa bisa ditutup. Tungkai kaki dan lengannya kecil,
kisut, dan kaku. Jemarinya hanyalah bulatan-bulatan, seperti bola-bola daging yang
ditancap asal-asalan. Ia tak punya cuping telinga dan batang hidung, hanya dua lubang
hitam di atas mulut dan dua lubang hitam di kiri-kanan wajahnya. Yang paling membuatku
tercengang adalah matanya. Warnanya merah darah. Sepasang mata itu tidak menjorok ke
dalam dan tidak berkelopak, tetapi berbentuk tonjolan yang mencelat keluar seperti dua
kelereng merah. Dari pemandangan yang tak terdefinisikan itu, aku hanya bisa mencatat
satu hal pasti. Kelaminnya laki-laki.
Dia ternyata masih hidup. Meski kaku seperti papan, bisa kudengar suara napasnya yang
mengorok.
“Adek…,” bisikku.
Bersamaan dengan itu, Ibu membalik badan. Mendapatiku tengah mematung di depan
bayi yang baru saja dilahirkannya.
“Zarah! Keluar kamu!” lengkingnya.
Aku menggigit bibir, menahan sedu sedanku. “Bu, biar Zarah pergi cari Ayah—”